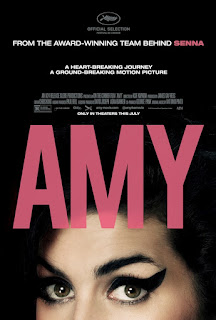Chief Content Officer Netflix,
Ted Sarandos, mengungkapkan bahwa film The
Ridiculous 6 yang diproduseri Adam Sandler dan tayang eksklusif untuk
Netflix mencetak rekor penayangan terbanyak selama 30 hari pertama film itu
dirilis. Sehebat apa The Ridiculous 6?
Apakah film tersebut begitu bagus secara kualitas hingga banyak menarik minat
penonton? Atau karena film itu terlalu jelek dan membuat banyak orang penasaran
dengan keburukannya? Saya akan membahasnya nanti, yang jelas, dalam film ini
tidak ada om-om bau keringat terjun ke sungai tanpa busana dan rusa yang buang
air kecil sembarangan seperti adegan pada
Grown Ups 2.
Tommy Stockburn (Adam Sandler), seorang ahli pisau yang
dibesarkan di keluarga Indian tanpa tahu siapa ayah kandungnya. sampai suatu
ketika perampok bank professional bernama Frank Stockburn (Nick Nolte)
mendatangi tempat tinggal Tommy, mengaku sebagai ayah kandungnya dan menginap
semalam di sana. Pagi harinya, sekelompok bandit datang ke desa Indian dan
menculik Frank dengan tebusan USD 50.000. Tommy berkelana untuk membebaskan
ayahnya. Sepanjang perjalanan, Tommy bertemu 5 orang putra Frank dari ibu yang
berbeda-beda, Chico (Terry Crews), Herm (Jorge Garcia), Lil’ Pete (Taylor
Lautner), Ramon (Rob Schneider), dan Danny (Luke Wilson). Keenam putra Frank
berpetualang bersama demi membebaskan sang ayah.
Jika dilihat dari sinopsis di atas, The Ridiculous 6 terlihat seperti kisah penculikan biasa. Dugaan
itu benar. Penculikan dan petualangan dalam durasi 119 menit sama persis dengan
peculikan ala FTV berkualitas rendah. Bedanya hanya pada usia korban
penculikan. Biasanya, FTV menampilkan seorang anak kecil lucu, imut, tak
berdosa, rajin belajar, patuh orang tua, jujur, terampil, setia, murah senyum,
hampir tidak pernah mengupil (hampir semua tayangan FTV tidak pernah
memperlihatkan orang mengupil. Padahal itu manusiawi dan anak kecil biasanya
hobi mengorek-orek hidung.) diculik oleh berandalan berwajah konyol dengan
jaket kulit lusuh, wajah pas-pasan, memakai celana denim tak terawat, berkulit
gelap, dan jarang mandi. Saya rasa ciri-ciri di atas mirip dengan diri saya.
Seperti film produksi Adam Sandler yang lain, The Ridiculous 6 Terlalu banyak
mengekspos kebodohan dan Kebodohan-kebodohan yang ditampilkan cenderung
mengganggu dan sukses mengurangi kadar kelucuan. Adam Sandler dengan
penampilannya yang terlihat seperti Nicholas Saputra sedang terserang muntaber
dan penuaan dini memperburuk kualitas film. Saya cukup mengapresiasi akting
Nick Nolte sebagai kakek-kakek nakal. Kehadirannya dapat menutupi kekurangan
pemeran-pemeran lain.
Sepanjang film, saya hanya tertawa satu kali ketika adegan
pencurian emas. Selebihnya, saya tidak terpikat dengan segala aspek kebodohan
dan kekonyolan ala Adam Sandler. Taylor Lautner sebagai petani culun juga telah
melanggar kaidah keculunan. Karena seorang culun harusnya tidak ganteng.
Sedangkan Lautner masih terlihat tampan walau karakternya culun.
Jika Anda penggemar berat Adam Sandler, The Ridiculous 6 wajib Anda saksikan karena semua bagian dalam film
ini merupakan akumulasi dari kebodohan, kekonyolan, absurditas, dan keanehan
film-film Sandler. Saya yakin, untuk memnonton film ini perlu tingkat kebodohan
yang luar biasa. Saya termasuk yang sedikit terhibur. Karena saya sedikit
bodoh.