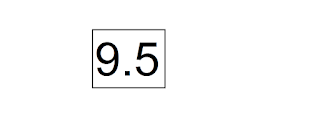Layanan streaming Netflix
selama ini terkenal dengan serial-serial superhero-nya
seperti Daredevil atau Jessica Jones. Namun, Netflix juga
banyak memproduksi serial komedi seperti Unbreakable
Kimmy Schmidt, Grace and Frankie, dan Master
of None. Kali ini saya akan membahas nama terakhir yang membawa seorang
Aziz Ansari, komika asal Amerika Serikat keturunan India, mendapat nominasi Goden Globe Awards dalam kategori aktor utama terbaik pada serial komedi.
Berkisah tentang kehidupan Dev (Aziz Ansari), seorang aktor
yang sedang meniti karir setelah lebih dahulu terkenal dalam iklan yogurt. Dev berjuang mengatasi berbagai
masalah kehidupan yang menghampirinya. Sama seperti artis NM dan PR yang diklaim dapat mengatasi masalah para pengusaha atau pejabat kaya yang sedang kekurangan kasih sayang
dari perempuan. Hubungan percintaan, karir sebagai aktor, menentukan tempat
makan, rasisme, hingga hubungan dengan orang tua adalah beberapa masalah yang
harus diatasi Dev. Sama seperti saya dan Anda yang pasti memiliki masalah.
Salah satu masalah terbesar saya adalah perut saya yang sering kurang
bersahabat. Saya curiga, jangan-jangan sebenarnya perut saya bukanlah sebuah
perut, melainkan seorang Setya Novanto yang bersembunyi dan menyamar sebagai
perut agar dia bisa menggerogoti semua makanan yang saya makan. Sama seperti
penggerogotannya ke tubuh DPR RI.
Sebelum menonton Master
of None, saya sebelumnya sudah selesai membaca buku karya Aziz Ansari dan
Eric Klinenberg, Modern Romance. Saya
tidak membaca bukunya karena bukunya terlalu mahal buat seorang jomblo
eknonomis (kere) seperti saya. Saya memilih untuk mengunduh buku elektroniknya
dengan konsekuensi harus menunggu lama karena koneksi internet yang lambat dan
harus menahan rasa sakit pada perut saya akibat terlalu banyak makan cilok
dengan sambal sebanyak lima sendok semen.
Modern Romance memiliki
keterkaitan yang kuat dengan Master of
None. Saya mencatat, ada empat episode yang mirip dengan isi buku Modern Romance. Salah satunya adalah episode
berjudul Old People yang membicarakan
tentang kehidupan para lansia. Salah satunya adalah nenek dari kekasih Dev,
Rachel (Noel Wells). Saya merasakan ikatan emosi yang kuat dalam episode
tersebut. Salah satunya karena nenek saya yang cukup unik dan wajib
dilestarikan. Bahkan kalau bisa nenek saya masuk ke dalam warisan-warisan dunia
yang harus dilestarikan, sama seperti batik dan Candi Borobudur.
Master of None berhasil
menggambarkan kehidupan dan permasalahan seorang laki-laki secara gamblang dan
sangat realistis. Dev memang sering kali melakukan kegiatan-kegiatan absurd,
namun absurditas itu dapat dimaklumi karena dalam dunia nyata, banyak orang
seperti Dev. Termasuk diri saya. Salah satu kegiatan absurd yang paling saya
ingat adalah ketika Dev dan sahabatnya, Arnold (Eric Wareheim) datang ke toko
mainan dan memencet boneka dinosaurus dengan terus-menerus disertai ekspresi
konyol. Jujur, saya juga sering melakukan kegiatan konyol seperti itu. Biasanya
saya bermain ciluk-ba dengan boneka Hello Kitty milik adik saya.
Aziz Ansari sebagai pemeran utama sukses membuat penonton
selalu memperhatikan segala ucapan dan tingkah lakunya. Tidak hanya itu,
karakter Dev menjadi semakin kuat dengan ekspresi-ekspresi jenaka khas Aziz
Ansari. Selain Aziz, kedua orangtua kandungnya, Shoukath dan Sharma Ansari yang
berperan sebagai orang tua Dev cukup mencuri perhatian. Terutama sang ayah,
Shoukath Ansari. Dialognya dengan Dev begitu mengena namun tetap menyenangkan.
Bagi saya, Master of None adalah
serial komedi terbaik yang pernah saya lihat. Jauh lebih baik dari serial
komedi yang terjadi di ruang sidang MKD.